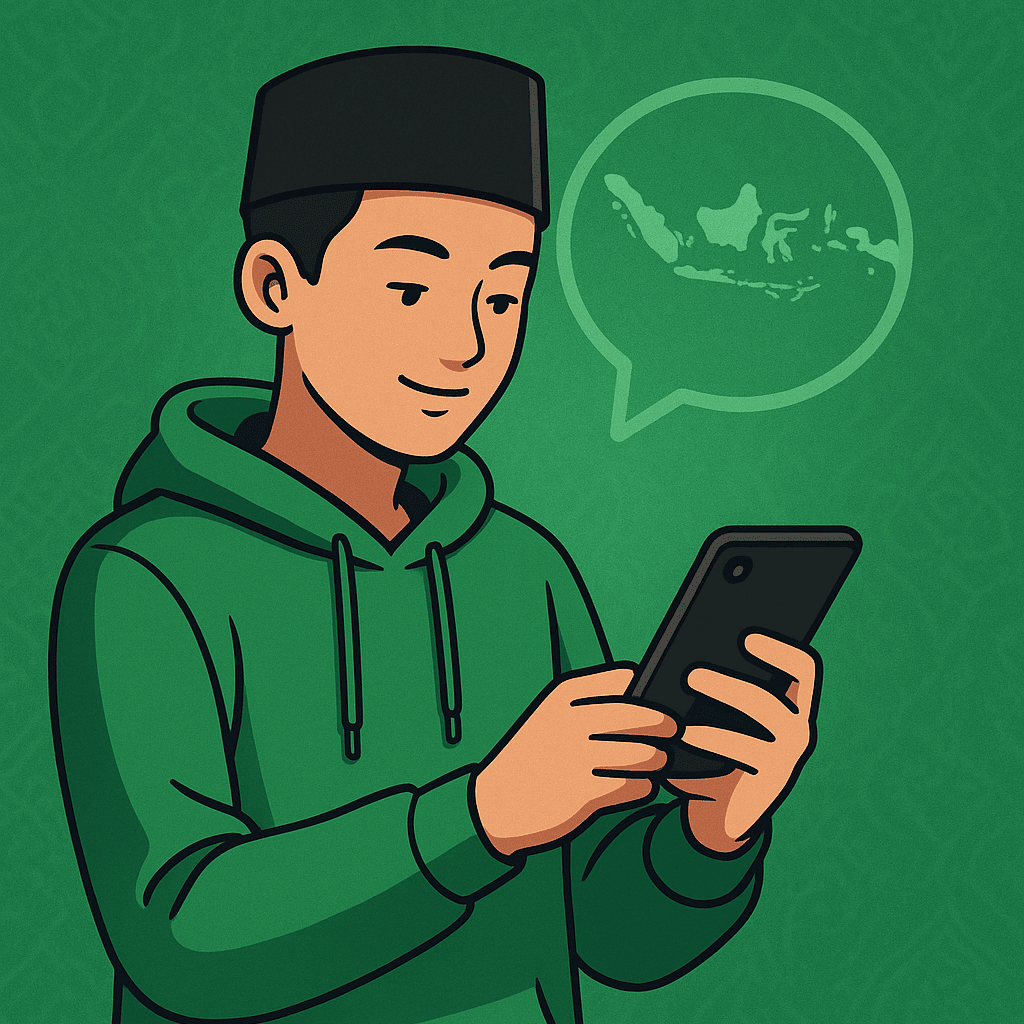Sosok Kiai visioner yang demokratis, bahkan dalam lingkup keluarganya sendiri. Ia memberi kebebasan penuh kepada anak-anaknya untuk menentukan jalan hidup. Sejak kecil, Wahid belajar di madrasah milik ayahnya, Kiai Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Daya ingatnya luar biasa, hingga di usia belia sudah dipercaya membantu sang ayah mengajar.
Ibunya yang berasal dari kalangan ningrat Jawa berharap anaknya menjadi sosok yang mampu menjembatani dunia pesantren dan masyarakat modern. Karena itu, meski anak pendiri pesantren, Wahid Hasyim justru diajak belajar bahasa Inggris dan Belanda kepada seorang manajer pabrik gula asal Eropa — hal yang sangat jarang di masa itu.
Pendidikannya berlanjut ke Makkah selama dua tahun. Sekembalinya ke Tebuireng pada 1934, ia membawa semangat besar untuk menggabungkan pendidikan modern dengan khazanah keislaman klasik. Melihat NU sebagai organisasi berbasis akar rumput, ia bertekad menghadirkan cendekiawan Muslim dari kalangan santri — agar pesantren tidak hanya melahirkan ahli kitab, tetapi juga pemimpin yang melek dunia.
Wahid Hasyim kemudian dikenal sebagai nasionalis terkemuka. Ia aktif di lingkaran elite pergerakan kemerdekaan bersama Soekarno dan Hatta. Putranya, Gus Dur pernah mengenang, ada seorang “Paman Hussein” yang sering datang ke rumah dan berbincang lama dengan ayahnya. Belakangan baru ia tahu, “Paman Hussein” itu adalah “Tan Malaka”. Hal itu menunjukkan betapa luas dan cairnya pergaulan Kiai Wahid, lintas ideologi dan latar belakang. Ia juga ikut dalam perumusan UUD 1945 dan Pancasila, bahkan sempat menjadi penasihat militer bagi Jenderal Sudirman di masa revolusi.
Sebagai Menteri Agama, Wahid Hasyim dikenal sederhana. Ia membesarkan anak-anaknya dengan kebebasan berpikir yang tinggi. Rumahnya ibarat ruang ilmu dan dialog, tempat berkumpulnya ulama, seniman, pejabat, dan wartawan asing. Buku, majalah, dan surat kabar menumpuk di setiap sudut, termasuk dari komunitas non-Muslim. Anak-anaknya bebas membaca apa pun dan didorong untuk berdiskusi terbuka. Baginya, santri harus berwawasan luas namun tetap berpijak pada nilai keislaman yang kokoh.
Gus Dur kecil sering ikut dalam pertemuan kenegaraan, melihat langsung bagaimana ayahnya berinteraksi dengan berbagai kalangan. Dari ayahnya, ia belajar tentang kesederhanaan, keterbukaan, dan sikap tidak membatasi diri. Kiai Wahid baginya adalah pribadi yang “gampangan” - mudah bergaul, tidak kaku, dan selalu mempermudah urusan orang lain.
Kiai Wahid Hasyim adalah bukti bahwa NU tak hanya kuat dalam amaliah, tetapi juga dalam keilmuan. Ia menunjukkan bahwa pesantren mampu melahirkan pemimpin bangsa tanpa kehilangan jati dirinya. Dari sosoknya, kita belajar bahwa Islam dan kebangsaan bukan dua hal yang bertentangan, melainkan jalan seiring dalam membangun peradaban Nusantara yang berakar, berilmu, dan berakhlak.
Selamat Hari Santri! Dari bilik pesantren, lahirlah cahaya yang menuntun negeri.
oleh: Muhammad Mustajib
Tumbuh bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Gresik